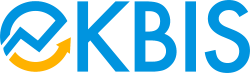EKBIS.CO, JAKARTA -- Masih banyak yang belum paham pentingnya kelestarian ekosistem gambut. Sehingga, diperlukan narasi bersama pengelolaan lahan gambut ini, supaya informasi yang diterima masyarakat tidak simpang siur. Usulan itu diutarakan Sony Mumbunan, pakar dari Pusat Riset Perubahan Iklim Universitas Indonesia (UI), dalam diskusi pakar bertajuk Perlindungan Gambut dan Pembangunan Ekonomi di Jakarta, Selasa (27/12) lalu.
“Di dalam gambut ada nilai ekonomi, dan gambut harus dijadikan sebagai input ekonomi untuk menghidupi masyarakat,” kata Sony Mumbunan.
Diskusi ini dihadiri Dr Suraya Afif dari Departemen Antropologi UI, Iwan Gunawan dari Bank Dunia, dan I Nyoman Suradiputra dari Wetlands Indonesia. Acara juga dihadiri Dr Myrna Asnawati Safitri, deputi III Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan Badan Restorasi Gambut (BRG).
Menurut Sony, narasi ekonomi konvensional melihat lahan gambut sebagai lahan kebun sawit. Padahal, ekosistem gambut juga memiliki nilai ekonomi yang menghidupi masyarakat. Konversi lahan gambut hanya akan meniadakan nilai ekonomi lahan gambut.
“Badan Restorasi Gambut (BRG) telah melakukan itu lewat budidaya tanaman yang ramah terhadap gambut, yaitu jelutung, sagu, nanas, dan purun. Tanaman-tanaman ramah ini disebut paludikultur,” ujarnya.
Narasi ekonomi yang menjadikan lahan gambut bernilai ekonomi jika ditanami komoditas ekspor, menurut I Nyoman Suradiputra, berujung pada hilangnya lahan gambut. Kehilangan ini dimulai dengan pembuatan kanal-kanal oleh pengusaha, yang menyebabkan terjadinya kekeringan lahan gambut.
“Kanal-kanal dibangun untuk mengeringkan gambut, agar lahan bisa ditanami sawit. Dampak buruk lainnya adalah penggunaan pestisida, yang merusak ekosistem lahan,” kata I Nyoman.
I Nyoman mengingatkan banyak pulau di pantai timur Sumatera terbentuk dari gambut. Pulau Padang dan Bengkalis salah satunya. Jika penanaman kelapa sawit dibiarkan di kedua pulau itu, lahan gambut akan amblas (subsidence), hilang, dan berpengaruh pada zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia.
Berbeda dengan Sony dan I Nyoman, Dr Suraya Afif secara serius mengomentari hasil kajian LPEM Universitas Indonesia (UI) yang menyebut PP 71 tahun 2014 Jo PP 57 tahun 2016 soal ekosistem gambut merugikan dunia usaha Rp 76 triliun. Menurutnya, kajian LPEM UI kekurangan review dan tidak netral.
“Kelihatan sekali keberpihakan terhadap pengusaha. Sebelum PP 71 keluar, pemerintah sudah mengeluarkan Keppres No 32 tahun 1990 tentang kawasan hutan lindung. Anehnya, kajian LPEM UI tidak mereview produk hukum ini," kata Suraya.
Ia juga mengkritisi hutan tanaman industri, dengan menyebutnya sebagai penyumbang cost paling besar dibanding keuntungan yang diperoleh. Land clearing, misalnya, menyebabkan hilangnnya keanekaragaman hayati. Belum lagi kebakaran hutan yang menimbulkan multiplier effect cost.
“Yang juga aneh tidak ada riset jangka panjang tentang efek biaya berkelanjutan akibat kebakaran hutan,” katanya.
Iwan Gunawan mengatakan setiap bencana menyebabkan gangguan pertumbuhan eonomi. Bencana kebakaran hutan, menurutnya, berdampak pada ketidak-seimbangan, gangguan terhadap prospek pembangunan, dan deficit yang harus ditutupi tidak cukup satu tahun anggaran.
“Akibatnya, landskap berubah dan pola distribusi juga berubah. Bencana kebakaran juga menyebabkan stock flow, atau aset yang rusak,” ujar Suraya.