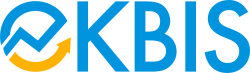EKBIS.CO, JAKARTA -- Serikat Petani Indonesia menyebut, minimnya lahan sawah padi mempengaruhi biaya produksi beras domestik. Sehingga jika dibandingkan dengan negara-negara produsen beras lainnya seperti Thailand dan Vietnam, harga beras Indonesia belum kompetitif.
Ketua Serikat Petani Indonesia Henry Saragih mengatakan, rata-rata lahan sawah petani padi di Vietnam dan Thailand seluas 2 hektare per petani, sedangkan lahan sawah yang dimiliki petani Indonesia hanya 0,3 hektare. Dengan disparitas luas lahan yang ada itu, kata dia, sangat wajar jika negara-negara produsen beras membanderol harga yang lebih kompetitif.
“Jadi persoalannya bukan di biaya produksi, ini permasalahan lahan saja,” kata Henry saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (19/7).
Henry menambahkan, minimnya lahan sawah padi yang diolah petani lokal juga karakteristiknya bukan kepemilikan pribadi. Artinya, masih banyak petani yang menyewa lahan untuk berproduksi. Dia menyebut, sejauh ini biaya produksi pertanian padi sudah cukup terjangkau.
Adapun biaya produksi gabah kering giling (GKG) di Indonesia berdasarkan catatannya mencapai Rp 20,16 juta per hektare sejumlah 5 ton atau sebesar Rp 4.030 per kilogram (kg). Sedangkan apabila dihitung secara rendemen GKG menjadi beras sebesar 50 persen, atau sekitar 2.500 kg beras. Sehingga biaya produksi GKG jika dikonversikan ke beras sebesar Rp 8.464 per kg.
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) luas lahan padi di Indonesia setelah dikoreksi berjumlah 7,06 juta hektare. Dengan jumlah tersebut, kata Henry, luas lahan sawah padi tidak sebanding dengan jumlah populasi masyarakat Indonesia sebesar 260 juta jiwa. Sehingga menurutnya, hal itu yang menjadi salah satu faktor kurang bersaingnya harga beras di kancah internasional.
Kendati demikian dia menilai, pemerintah tidak perlu berambisi mengejar pangsa ekspor meski permintaan terhadap beras domestik ada. Menurut dia, saat ini produksi beras dalam negeri cukup dikonsumsi sendiri sehingga dapat mengurangi porsi beras impor.
“Kita inginnya dikonsumsi saja dulu di dalam negeri, tidak perlu ekspor,” kata Henry.
Dia mencontohkan, konsumsi beras lokal juga perlu dimanfaatkan industri untuk keperluan makanan olahan seperti mie. Karena jika dibandingkan dengan kondisi konsumsi di jaman dahulu, peran beras saat ini justru tak terserap dengan baik ke industri.
“Beras broken dan menih itu kalau dulu dipakai jadi bahan baku mihun dan mie oleh industri, tepung beras. Sekarang mereka (industri) pakainya gandum,” kata dia.
Di sisi lain, dia juga berharap rantai niaga beras di Indonesia tidak terlalu panjang. Sehingga ke depan, diharapkan petani dapat menjangkau pasar eceran dengan rantai niaga pendek sehingga dapat memberikan nilai tambah dan keuntungan yang lebih.
Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agro Ekologi Serikat Petani Indonesia Qomar menyampaikan alasan mengapa beras Vietnam dan Thailand murah. Menurut dia, sebagian besar beras Vietnam dan Thailand itu justri merupakan beras impor asal Kamboja yang selalu surplus beras sebab luas lahannya mendukung.
"Sedangkan konsumsi beras mereka (Kamboja) per kapita lebih sedikit,” kata dia.
Menurutnya, karena faktor tersebut sangat memungkinkan bagi Kamboja untuk menjual beras dengan harga murah meski keuntungan yang diperoleh petaninya sangat minim. Dia mengatakan, para petani padi di Kamboja hanya meraup keuntungan rata-rata Rp 300 ribu per hektare per musim.
Hal itu dinilai membuat kondisi petani Kamboja berada dalam kondisi sulit, terlebih dengan adanya perdagangan bebas. Sehingga, mau tidak mau beras Kamboja diekspor ke Thailand dan Vietnam dengan harga yang rendah.
Dia menambahkan, jika Indonesia memang serius untuk melakukan ekspor beras, seharusnya yang ditarget adalah pasar-pasar ekspor untuk beras kualitas premium. Bukan justru melakukan ekspor beras dengan murah dan bersaing dengan negara-negara yang surplus beras. Saat ini, kata dia, lebih baik pemerintah fokus mendistribusikan produk-produk petani untuk pasar lokal.