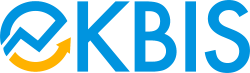EKBIS.CO, JAKARTA – Pengamat Ekonomi yang juga Direktur Next Policy Yusuf Wibisono menilai kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen merupakan langkah pintas pemerintah untuk bisa mencapai target penerimaan pajak. Ia menyayangkan kenaikan pajak tersebut, berkaca dari merosotnya tax ratio dalam satu dekade terkhir, terlebih kondisi daya beli masyarakat saat ini sedang melemah.
“Kenaikan PPN menjadi 11 persen per April 2022 dan kini direncanakan akan menjadi 12 persen per Januari 2025 terlihat menjadi kebijakan ‘jalan pintas’ pemerintah demi mengejar target kenaikan penerimaan perpajakan,” kata Yusuf kepada Republika, Senin (16/9/2024).
Yusuf menjelaskan, kinerja penerimaan perpajakan mengalami penurunan dalam 10 tahun belakangan. Menurut catatannya, di akhir periode Presiden SBY pada 2014 tax ratio berada di kisaran 10,85 persen dari produk domestik bruto (PDB), sedangkan di akhir periode pertama Presiden Joko Widodo pada 2019 tax ratio turun tajam menjadi hanya 9,77 persen dari PDB. Di waktu yang sama, penerimaan PPN turun dari 3,87 persen dari PDB pada 2014 menjadi 3,36 persen dari PDB pada 2019.
“Lahirnya UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan/ UU Nomor 7 Tahun 2021) atau omnibus law perpajakan pada 2021, yang menjadi dasar kenaikan tarif PPN, terlihat untuk mendongkrak kinerja penerimaan perpajakan ini,” ujar Yusuf.
Lantas, pascakenaikan tarif PPN menjadi 11 persen pada 2022, penerimaan PPN meningkat dari 3,25 persen dari PDB pada 2021 menjadi 3,51 persen dari PDB pada 2022, dan terakhir menjadi 3,62 persen dari PDB pada 2023.
Namun tax ratio secara keseluruhan hanya meningkat pada 2022, dari 9,12 persen dari PDB pada 2021, menjadi 10,39 persen dari PDB pada 2022. Sedangkan pada 2023, tax ratio turun menjadi 10,21 persen dari PDB.
“Terlihat bahwa kinerja PPN yang meningkat pascakenaikan tarif justru diikuti menurunnya kinerja pajak lainnya terutama PPh. Penerimaan PPh yang awalnya meningkat dari 4,10 persen dari PDB pada 2021 menjadi 5,10 persen dari PDB pada 2022, pada 2023 stagnan menjadi 5,03 persen dari PDB,” terangnya.
Yusuf menilai, setelah kenaikan tarif PPN menjadi 11 persen pada 2022 terlihat tendensi awal bahwa peran penerimaan PPN dalam penerimaan perpajakan semakin menguat. Menurutnya, jika itu berlanjut, akan berpotensi memperburuk kesenjangan pendapatan karena PPN lebih bersifat regresif dibandingkan PPh.
PPN diketahui lebih bersifat regresif karena dibayarkan saat pendapatan dibelanjakan untuk barang dan jasa dengan tarif tunggal, terlepas berapapun tingkat pendapatan masyarakat.
“Maka, tanpa ada perubahan kinerja penerimaan PPh, rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen pada 2025 berpotensi besar akan memiliki dampak redistributif yang lebih kuat, dengan hasil akhir kesenjangan akan meningkat,” ungkapnya.
Yusuf menerangkan, tarif PPN 10 persen telah bertahan sekitar empat dekade, sejak 1983—2021. Ia mengaku menyayangkan bergulirnya kenaikan PPN yang tidak dibarengi dengan penguatan daya beli masyarakat yang saat ini tengah melemah.
“Kita menyesalkan langkah menaikkan tarif PPN menjadi 11 persen pada 2022 dan kini 12 persen pada 2025, ditengah lemahnya daya beli masyarakat terutama kelas bawah dan menengah, serta di tengah belum optimalnya upaya meningkatkan basis perpajakan terutama basis PPh dari kelas terkaya, yang selama ini under-tax,” jelasnya.
Lebih lanjut, Yusuf menuturkan, kenaikan tarif PPN pada 2025 akan terjadi di tengah tekanan pengeluaran negara yang sangat besar. Termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), Proyek Strategis Nasional (PSN) dan megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN), serta berhadapan dengan tax ratio yang stagnan meski telah melakukan sejumlah besar reformasi perpajakan termasuk tax amnesty.
“Hal ini membuat kenaikan tarif PPN menjadi terlihat seperti jalan pintas untuk menaikkan tax ratiodan ruang fiskal. Masuknya program populis Presiden Prabowo yaitu program MBG pada APBN 2025 semakin menguatkan rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen pada 2025,” ungkapnya.