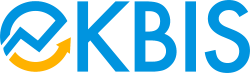EKBIS.CO, Oleh : Sunarsip
Amy Chua, seorang profesor dan pengacara (lawyer) berkebangsaan Amerika Serikat dan beretnis China menulis buku World on Fire: How Exporting Free Market Democracy Breeds Ethnic Hatred and Global Instability.
Dalam bukunya, Chua mengatakan, bahwa “when free market democracy is pursued in the presence of a market-dominant minority, the almost invariable result is backlash. This backlash typically takes one of three forms. The first is a backlash against markets, targeting the market-dominant minority’s wealth. The second is a backlash against democracy by forces favorable to the market-dominant minority. The third is violence, sometimes genocidal, directed against the market-dominant minority itself.”
Kalau diterjemahkan secara bebas, pernyataan Chua tersebut mengandung arti bahwa penerapan demokrasi dalam kondisi dimana minoritas mendominasi (lebih makmur) secara tidak proporsional, dimana pun hasilnya akan relatif serupa yaitu berpotensi terjadi reaksi balik (backlash) yang merugikan bagi kelompok minoritas. Reaksi balik ini dapat bermacam-macam. Pertama, reaksi balik terhadap pasar dengan sasaran kaum makmur minoritas. Kedua, reaksi balik melawan demokrasi dengan memberi tekanan kepada kaum minoritas. Ketiga, dapat berbentuk kekerasan (violence), dimana pada kasus tertentu dapat terjadi genosida terhadap kaum minoritas.
Pernyataan Chua ini memang terbilang kontroversial dan “berani” karena mengaitkan ketimpangan ekonomi yang terjadi antara kelompok minoritas (yang mapan) dengan kelompok mayoritas (yang kurang beruntung) terhadap masa depan demokrasi. Namun, kalau kita cermati empiris konflik yang terjadi, khususnya di Indonesia, sepertinya tesis Chua tersebut relevan untuk dikaji. Konflik 1998 di Indonesia, misalnya, kalau kita telusuri akar masalahnya juga tidak jauh dari persoalan ketimpangan ekonomi antara kelompok minoritas mapan dengan kelompok mayoritas kurang beruntung, sehingga kita menyaksikan bahwa banyak saudara-saudara kita yang berlatar belakang etnis China saat itu yang menjadi korban.
Kalau kita mencermati hangatnya situasi politik terutama sejak pemilihan presiden 2014 dan kini berlanjut pada pemilihan Gubernur di DKI Jakarta, pemicunya juga kira-kira hampir sama. Patronase antara kekuasaan politik dan ekonomi telah terjadi sejak lama di Indonesia. Namun, terdapat perbedaan yang mendasar antara era saat ini dengan di era Orde Baru dan sebelumnya. Pada era Orde Baru dan sebelumnya, panggung politik kelompok minoritas terbatas atau bahkan sengaja dibatasi oleh penguasa. Sebagai “kompensasinya”, kelompok minoritas diberikan kemudahan dan terkesan eksklusif dalam akses ekonomi. Kini, dengan berlakunya Undang-undang (UU) No. 40/2008, setiap warga negara memiliki hak yang sama baik di bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya tanpa ada pembedaan ras dan etnis.
Masalahnya adalah, ketika kesamaan perlakuan (equal treatment) hendak diberlakukan dalam segala aspek, fakta menunjukkan adanya ketimpangan antara kelompok minoritas dan kelompok mayoritas terutama secara ekonomi. Modal dasar ekonomi (berupa kemakmuran) yang dimiliki kelompok minoritas sudah jauh meninggalkan kelompok mayoritas. Dalam terminologi ekonomi pasar, hambatan (barrier) telah tercipta lebih dulu bagi pelaku ekonomi (dan politik) yang modalnya kecil untuk masuk ke dalam pasar ekonomi (dan politik). Pasar politik sudah tidak memungkinkan terjadinya persaingan sempurna (perfect competition), karena pasar politik sudah dimonopoli oleh kelompok minoritas yang mapan (secara ekonomi).
Harus diakui, munculnya tokoh-tokoh bisnis dari kelompok minoritas mapan yang terbaca oleh publik telah menjadi pendukung kekuatan politik tertentu bahkan terlibat langsung dalam perebutan kekuasaan politik, sedikit banyak ikut menjadi pemicu menghangatnya situasi politik saat ini. Terlebih lagi, tokoh-tokoh bisnis tersebut ditengarahi pada masa lalunya memperoleh kemakmuran karena hak eksklusif dari penguasa. Tuntutan adanya “keadilan” pun bermunculan. Negara dituntut agar mengoreksi ketidakadilan tersebut.
Terkesan tidak adil (fair) memang bila equal treatment dituntut diberlakukan dalam segala aspek bagi setiap warga, di saat yang sama modal ekonominya sudah jauh timpang. Karenanya, sejalan dengan pemberlakuan equal treatment, pemerintah perlu mengoreksi ketimpangan ini. Tujuannya, untuk mencegah terjadinya reaksi balik (backlash) yang dapat merugikan kelompok minoritas dan masa depan demokratisasi itu sendiri.
Ketimpangan ekonomi kita memang nyata. Kegiatan pembangunan ekonomi berhasil mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Akan tetapi, kenaikan rasio gini menunjukkan ketimpangan yang memburuk, yaitu dari 0,31 (1999) menjadi 0,40 (2016). Penting dicatat bahwa rasio gini tersebut diukur berdasarkan distribusi konsumsi per-kapita. Angka ketimpangan akan lebih tinggi lagi jika diukur dengan distribusi pendapatan (income) apalagi dengan distribusi kekayaan (wealth).
Dalam hal konsentrasi kekayaan, posisi Indonesia terburuk keempat setelah Rusia, India, dan Thailand. Dimana, 1 persen penduduk terkaya di Indonesia mengontrol sekitar 49,3 persen kekayaan secara nasional. Lahan mayoritas juga dikontrol oleh pengusaha tertentu. Saat ini, terdapat 14,6 juta atau sekitar 56 persen dari total rumah tangga usaha pertanian (RTUP) yang menguasai lahan kurang dari 0,50 hektar (5.000 m2). Di sisi lain, ada satu kelompok usaha yang mengendalikan lahan perkebunan yang luasnya melebihi luas Singapura.
Pemerintah sebenarnya telah menyadari adanya ketimpangan ini. Pemerintah pun kini sedang merancang kebijakan untuk mengoreksi ketimpangan tersebut. Konfigurasi kebijakan ekonomi baru yang akan diambil pemerintah bertumpu pada tiga aspek: lahan, kesempatan, dan kapasitas SDM. Saya berpendapat bahwa karena kebijakan ini sifatnya korektif, tentunya harus bersifat afirmasi (affirmative) dengan sasaran kelompok masyarakat yang ditentukan bukan kebijakan yang bersifat umum.
Kebijakan afirmasi sebenarnya bukan hal yang baru dan tidak perlu dikhawatirkan. “Diskriminasi” kebijakan memang akan muncul dalam pemberlakuan kebijakan korektif ini, namun tetap dapat dijaga dalam koridor yang market friendly seperti yang diterapkan di Malaysia. Kebijakan yang berorientasi pada pribumi di Malaysia, misalnya, sasarannya adalah peningkatan kesejahteraan dan kapasitas SDM pribumi yang memang tertinggal. Kebijakan yang dilakukan, misalnya, kewajiban bagi perusahaan yang baru didirikan agar mayoritas kepemilikan saham oleh pribumi (minimal 70 persen).
Kemudian, lahan-lahan perkebunan yang telah habis masa kontraknya diberikan konsensinya mayoritas kepada pribumi. Meskipun terkesan diskriminatif, namun sama sekali tidak ada penolakan dari kelompok non-pribumi. Sebab, sasaran kebijakan afirmasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Pribumi tanpa mengurangi dan mengambil hak-hak non-pribumi yang saat ini telah dimilikinya.
Dalam konteks Indonesia, dikotomi pribumi dan non-pribumi sebenarnya sudah tidak diakui lagi karena UU No. 40/2008 telah melarangnya. Namun, bukan rahasia lagi bahwa kesenjangan ekonomi terjadi pada kelompok-kelompok tersebut. Oleh karenanya, agar kebijakan korektif ini bisa efektif, sasaran implementasinya harus jelas pada kelompok yang saat ini kurang beruntung. Sebab, tanpa kebijakan afirmatif yang jelas sasarannya, sulit kebijakan tersebut dapat berhasil.