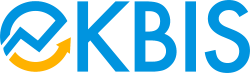EKBIS.CO, JAKARTA -- Ekonom INDEF Dradjad Wibowo menilai utang Pemerintah Indonesia tidak aman, jika dilihat dari sudut penerimaan negara. Namun, utang pemerintah ini aman kalau dilihat secara ekonomi makro.
Terkait dengan masalah utang, Dradjad menjelaskan bahwa masyarakat sering rancu membedakan utang pemerintah dan utang negara. Yang disebut utang pemerintah adalah utang yang dilakukan pemerintah. Sementara, utang negara adalah utang pemerintah ditambah dengan utang korporasi, termasuk BUMN.
"Tolok ukurnya yang klasik dalam ekonomi makro adalah 'rasio utang pemerintah terhadap PDB'. Istilahnya public-atau government-debt ratio (GDR)," kata Dradjad, Rabu (14/3).
Jika ukurannya GDR, kata Dradjad, posisi GDR tahun 2017 itu 29,2 persen. Ini “sangat rendah”. Bahkan, di antara G20, Indonesia adalah negara kedua yang paling rendah GDR-nya. "Yang paling rendah itu Rusia, hanya 12,6 persen pada tahun 2017," ungkap anggota Dewan Kehormatan PAN ini.
Yang paling tinggi adalah Jepang (250,4 persen), Italia (131,5 persen), dan Amerika Serikat (105,4 persen).
GDR Indonesia juga masih jauh di bawah India (69,5 persen) dan China (46,2 persen).
Apakah aman? Dradjad mengatakan, ini agak lebih njlimet melihatnya. Aman itu artinya pemerintah mampu membayar utang yang jatuh tempo, baik pokok maupun bunganya.
"Sumbernya (untuk membayar--Red) ada tiga, yaitu aset dan tabungan pemerintah, penerimaan pemerintah, dan utang baru. Di Indonesia, penerimaan pemerintah ini dalam APBN disebut penerimaan negara, baik pajak maupun bukan pajak," papar Dradjad.
Jepang dan AS dengan tingkat GDR yang supertinggi itu, kata Dradjad, tergolong masih aman. Hal ini karena, pertama, rasio penerimaan pajak Jepang terhadap PDB (rasio pajak) tinggi. Rasio pajak Jepang sekitar 36 persen dan AS 26 persen.
Kedua, investor dunia memiliki kepercayaan yang sangat tinggi kepada kedua negara ini sehingga cenderung terus membeli surat utang baru mereka. Padahal, bunga surat utang mereka relatif sangat rendah.
"Faktor kedua ini, yaitu kepercayaan, sangatlah krusial," kata Dradjad. Jadi, GDR Jepang dan AS aman karena penerimaan pajaknya tinggi dan mereka dipercaya investor.
Sementara itu, lanjut Dradjad, rasio pajak Indonesia terus berkutat di level 11-12 persen. Ini yang terendah di G20. Bahkan, tergolong rendah di dunia. "Padahal, pajak penghasilan di Indonesia tergolong tinggi di dunia, lumayan memberatkan perusahaan dan orang pribadi," ungkapnya.
Artinya, penghasilan pemerintah sendiri dalam membayar utang itu sangat rendah untuk ukuran dunia. Mau tidak mau, Indonesia harus mengandalkan investor membeli surat utang baru.
Di situlah letak masalahnya. Dijelaskannya, pada 2017, misalnya, realisasi penerimaan negara pajak dan bukan pajak itu Rp 1660 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 31 persen habis untuk membayar pokok dan jumlah utang. Jumlah yang sangat besar.
Yang lebih ironis, kata Dradjad, pemerintah menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai program andalan. Pada 2018, anggaran infrastruktur dinaikkan menjadi Rp 409 triliun.
Meski anggaran infrastruktur itu kelihatan besar, ternyata anggaran ini jauh lebih kecil jika dibanding untuk pembayaran utang. Pada 2017 saja, kata Dradjad, pemerintah harus membayar pokok dan bunga utang lebih dari Rp 510 triliun.
"Artinya, program andalan itu bukan infrastruktur, tapi pembayaran utang dengan anggaran Rp 100 triliun di atas infrastruktur. Jadi, ada ketimpangan besar dalam alokasi anggaran," kata ekonom senior ini.
Yang lebih serius lagi, lanjut Dradjad, beban pembayaran utang di atas itu adalah untuk membayar utang yang dibuat pemerintah sebelumnya. Padahal, sebelum ini GDR Indonesia hanya sekitar 23 persen. Dengan GDR yang makin tinggi, pemerintah sekarang memberikan beban yang lebih berat kepada pemerintah mendatang.